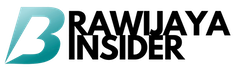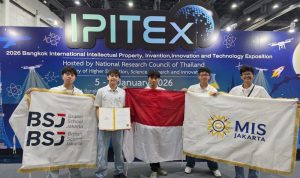Surabaya, – Sistem pembayaran digital nasional QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ternyata tak hanya mencuri perhatian masyarakat dalam negeri, tetapi juga memicu keresahan di level global. Menurut Prof. Henri Subianto, pakar komunikasi dan kebijakan publik dari Universitas Airlangga, tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam isu ini bukanlah isapan jempol.
“QRIS ini bukan sekadar alat transaksi. Ia simbol kemandirian digital nasional. Dan itu tidak disukai oleh kekuatan global yang selama ini mengontrol arus data dan transaksi keuangan internasional melalui Visa, Mastercard, dan perusahaan teknologi Barat lainnya,” ujar Prof. Henri dalam wawancara khusus, Kamis (24/4/2025).
Surveillance Capitalism Terancam
Prof. Henri menyebutkan, QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan telah digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia menjadi momok bagi kapitalis global. Masalah utamanya bukan sekadar potensi hilangnya keuntungan, melainkan karena QRIS menutup akses mereka terhadap data transaksi warga Indonesia.
“Data adalah emas baru. Kalau QRIS dikelola dan disimpan sepenuhnya di dalam negeri, itu artinya mereka tidak bisa memata-matai perilaku konsumen kita. Dan itu jelas bertentangan dengan model surveillance capitalism yang selama ini dijalankan perusahaan-perusahaan raksasa dunia,” ungkapnya.
Dari Trump Sampai Tekanan Aturan
Tak berhenti di situ, tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia juga berkaitan dengan kebijakan lokalisasi data. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012, semua pusat data wajib berada di Indonesia. Namun, PP ini kemudian diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2019, yang membuka pintu lebar bagi pusat data asing.
“Perubahan itu bukan kebetulan. Oktober 2019, pejabat tinggi AS datang ke Indonesia. Mereka melobi habis-habisan agar aturan diubah. Dan berhasil. Pasal 17 yang semula mengharuskan pusat data di dalam negeri, dihapuskan. Sekarang? Google, WhatsApp, bahkan X bebas menyimpan data di luar negeri tanpa tunduk pada tata nilai kita,” jelas Prof. Henri.
Ia menambahkan, infrastruktur digital nasional kini jadi medan pertempuran yang tak kasat mata.
“QRIS dianggap ancaman karena melawan arus liberalisasi data global yang selama ini menguntungkan negara-negara maju,” tandasnya.
US CLOUD Act: Ancaman Kedaulatan Digital
Masalah makin pelik ketika undang-undang (UU) US CLOUD Act diberlakukan oleh Pemerintahan Trump pada 2018 lalu. UU ini mewajibkan seluruh perusahaan teknologi asal AS menyerahkan data pelanggannya ke pemerintah AS, di mana pun data itu disimpan.
“Artinya, kalau kita pakai layanan seperti Facebook, Gmail, atau Amazon—maka data kita otomatis bisa diakses Washington. Ini bukan paranoid, ini fakta hukum,” kata Prof. Henri tegas.
Lebih mencemaskan lagi, China pun ikut-ikutan. Tahun 2021, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan Data Security Law (数据安全法 / Shùjù Ānquán Fǎ) yang memiliki semangat serupa: semua data yang dikuasai perusahaan China bisa diakses oleh pemerintahnya.
“Jadi baik AS maupun RRC sebenarnya punya agenda serupa yakni mengendalikan informasi dunia. Maka QRIS menjadi ujian serius bagi Indonesia—apakah kita benar-benar berdaulat secara digital atau justru terus jadi sasaran eksploitasi data oleh negara besar,” ujarnya.
Menanti Sikap Tegas Pemerintah
Di tengah situasi sedemikian rupa tersebut, Prof. Henri berharap Presiden Prabowo Subianto menyadari pentingnya kedaulatan digital.
“Jangan kita terlalu sering ‘mengalah’ dan ‘dibodohi’. QRIS adalah contoh bahwa kita bisa mandiri. Tapi pertanyaannya sekarang maukah pemerintah mempertahankan itu, atau tunduk lagi pada tekanan asing?” tandasnya Prof Henri retoris.
(Tommy/Sulaiman)