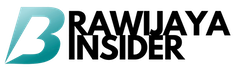Surabaya, Jawa Timur – Latar belakang sastra tidak pernah membatasi langkah Anisa Farida. Alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga itu justru menapaki jalan panjang diplomasi, mengabdi hampir 16 tahun di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan fokus kuat pada isu kemanusiaan dan perlindungan warga negara.
Lulus pada 2007, Anisa tak pernah membayangkan dirinya akan menjadi diplomat. Dunia sastra yang digelutinya kala itu lebih sering dipautkan dengan profesi pengajar, penerjemah, atau pekerja pariwisata. Namun setahun kemudian, atas dorongan rekan-rekannya, ia mengikuti seleksi calon diplomat Kemlu RI. Tanpa ekspektasi berlebih, Anisa justru lolos dan resmi bergabung pada akhir 2008.
Karier Anisa dimulai pada 2009 melalui Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu). Tanpa latar belakang hubungan internasional maupun hukum, ia harus membangun pemahaman diplomasi dari titik paling dasar.
“Waktu masuk itu benar-benar dari nol. Saya bukan dari HI atau hukum, jadi semua cara berpikir diplomasi itu baru. Tapi ada pelatihan berjenjang, jadi pelan-pelan terbentuk,” tuturnya.
Penugasan luar negeri pertamanya membawanya ke Toronto, Kanada. Dalam masa magang tersebut, Anisa terlibat dalam berbagai urusan kekonsuleran dan kegiatan kemanusiaan, termasuk penggalangan dana bersama komunitas Indonesia dan simpatisan internasional. Di sanalah ia mulai bersentuhan langsung dengan persoalan kemanusiaan lintas negara.
Diplomasi yang Berhadapan dengan Manusia
Sekembali ke Indonesia, Anisa bergabung dengan Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu RI. Ketertarikannya pada isu HAM pun kian menguat, terutama terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Penugasan di London, Inggris, menjadi salah satu fase paling menantang. Di sana, ia menangani berbagai kasus konsuler, termasuk pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan, eksploitasi, hingga kerja paksa.
“Di London tekanannya terasa sekali. Kita berhadapan langsung dengan orang, bukan cuma dokumen. Telepon bisa masuk kapan saja, dan kita harus langsung berpikir, apa yang harus dilakukan, dampaknya ke orang ini apa,” ujarnya.
Salah satu pengalaman paling membekas adalah keterlibatannya dalam proses pemulangan seorang pekerja migran perempuan yang tak pulang ke Indonesia selama 18 tahun karena disekap majikannya. Pengalaman itu, menurut Anisa, mempertegas makna kehadiran negara bagi warganya.
“Di situ saya benar-benar merasa, inilah fungsi negara. Ketika seseorang berada di posisi paling rentan, negara harus hadir,” katanya.
Usai penugasan di London, Anisa kembali ke Jakarta dan bertugas di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Meski berbeda isu, pekerjaannya tetap bersinggungan dengan HAM. Pada 2022, ia kembali ditugaskan ke luar negeri, kali ini ke Jenewa, Swiss.
Di Jenewa, Anisa menangani isu perdagangan internasional dalam forum multilateral—bidang yang sama sekali baru baginya. Ia kembali menjadi pembelajar.
“Awalnya saya merasa keluar dari jalur yang sudah saya bangun. Tapi ternyata isu perdagangan ini menarik, karena hasil negosiasinya mengikat dan ada mekanisme penegakannya. Dampaknya terasa langsung,” jelasnya.
Pengalaman tersebut mengubah cara pandangnya tentang diplomasi. Jika sebelumnya ia banyak bergulat dengan norma dan nilai, kini ia melihat diplomasi juga sebagai instrumen strategis dengan konsekuensi nyata bagi negara.
“Kalau kita salah negosiasi, dampaknya langsung terasa. Hidup itu proses belajar seumur hidup. Kalau berhenti belajar, kita akan berhenti berkembang,” ucapnya.
Perjalanan Anisa Farida menunjukkan bahwa Universitas Airlangga tidak hanya melahirkan alumni berprestasi, tetapi juga insan yang mampu berkontribusi nyata di panggung global dengan empati, ketekunan, dan keberanian untuk terus belajar.(*)
(Khefti/Sulaiman)